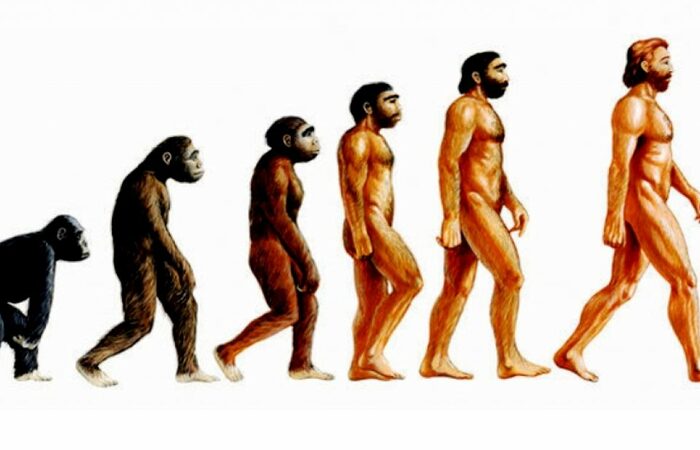(Photo: Tempo.co)  Salah seorang temen tanya “klo Muhammadiyah yang bakar bendera gimana?†terus gua tanya balik, “sejak kapan saya mengomentari pilihan aliran kepercayaan seseorang?†satu-satunya aliran kepercayaan yang menarik minat kritik saya adalah “kepercayaan bahwa kebenaran ada pada objek†yaitu objectivism. “memangnya kenapa? Apa yang salah?â€pasalnya tidak ada satu kepercayaan yang boleh lebih tinggi dari pada yang lainnya, hierarkis kepercayaan menuntut prioritas tindakan. Objectivism sebagai sebuah metodologi kebenaran bermanfaat bagi developmentalism, tapi tidak berhak menegasikan kepercayaan lainnya karena ia juga setara dengan yang lain.
Sekarang saya mau sampaikan, klo memang Muhammadiyah lakukan itu, saya akan gunakan seluruh kemampun saya untuk melawannya saat itu (dalam maupun luar). Hari ini bentuk perlawanan saya adalah serat kalimasada atau tulisan. Salah satu kritik utama terhadap objectivism adalah etika utilitarianism, yang bagi Sartre tidak ada satupun alasan kita untuk menyakiti minoritas ataupun orang yang berbeda pandangan, diktumnya sederhana “aku mungkin berbeda pendapat denganmu tapi ku bela hakmu berpendapatâ€. Bagi saya satu tindakan yang dilkukan mayoritas terhadap minoritas akan menjadi contoh yang teramat melekat, jika itu dianggap baik maka akan memperoleh dukungan dari minoritas, tetapi apabila buruk maka revenge akan muncul,, parahnya jika revenge itu diorganisir sehingga sanggup membalik yang mayoritas tadi mmenjadi minoritas, akhirnya yang terjadi adalah ilustrasi Soekarno dalam siding BPUPKI sambil mengutip Jean Jaures,
“wakil kaum buruh yang punya hak politik itu, di dalam parlemen akan menjatuhkan minister. Ia seperti raja! …… sekarang ia seperti raja, bersok dia di lempar ke luar ke jalan raya, dibikin werkloos, tidak makan suatu apa.â€
Kemudian Soekarno bertanya, apakah keadaan demikian yang kita kehendaki?
Sekarang izinkan saya bertanya hal yang sama, apakah keadaan saling balas inilah yang kita kehendaki? Tidakkah cukup fasilitas istimewa didapatkan oleh mayoritas? Wajar jikalau tanggungjawab lebih besar diemban mayoritas, apa itu? tanggungjawab untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi minoritas. Sebuah kewajaran yang sama bagi minoritas untuk melawan, tapi kalau mayoritas lawan balik? Itu namanya konyol, karena anda membuat mayoritas terpecah, kelak justru banyak yang beralih membela minoritas kemudian andalah yang terasing.
Dalam kasus pembakaran bendera ini saya lebih concern pada perluasannya, sembari melakukan kritik terhadap objectivism yang kehilangan moralitas demi mayoritas, dalilnya “The Winner Takes Allâ€. Dalam utilitarianisme anda diperbolehkan mengolok-ngolok satu orang untuk kebahagiaan banyak orang. Bagi saya Nasionalisme itu imajiner, ia kerapkali berubah karena ditopang sumbernya yakni rakyat, sedangkan rakyat yang cerdas akan berubah, maka nasionalisme mestilah beradaptasi dengan perubahan itu. Atau kita mau nasionalisme yang tertutup? Hingga munculnya chauvinism? Tak mesti saya kutip lagi wejangan Soekarno tentang nasionalisme yng tumbuh subur di taman internasionalim.
Saya bukan tidak mau peduli arti dari simbol “Laa Ilaha Illa Allahâ€, tapi debat kepercayaan adalah ruangan hampa yang tak pernah menemui ujung. Saya juga tidak sedang membandingkan symbol satu dengan yang lainnya, bahkan untuk sekedar ide pun saya anggap berada pada konteks perdebatan yang berbeda. Tapi tindakan bar-bar jelas pada konteks apapun tidak diperkenankan! Bagaimana dengan revolusi?
Dalilnya saya kutip dari tokoh realism, lewat contract social atau “pactum unions†rakyat memberikan mndat pada negara, jika negara tidak sesuai keinginan rakyat, maka rakyat punya hak Revolusi. Hak tersebut kata John Locke mesti dilindungi oleh Negara commonwealth, sedangkan menurut Easton sistem politik harus dipandang utuh, ia haruslah terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan baru, karena ujiannya memanglah begitu. Klo ia berubah maka perubahannya akan diarahkan pada kemajuan, jika tuntutan tidak cukup kuat untuk masuk pada meknisme politik maka ia akan terlempar dengan sendirinya.
Bagi anda pejuang demokrasi dan liberalism tentu pandangan demikian tidak aneh, apalagi jika anda bermaksud mengintegrasikan Islam dan Demokrasi sebagaimana yang dilakukan oleh gerakan populisme, atau jangan-jangan anda juga hanya memnfatkan Islam sebagai symbol? Sebuah identitas untuk menarik masyarakat agar berpihak pada anda? Seperti apa yang dikemukakan oleh Azumardi Azra, “kini pada masa reformasi, friksi dan pembelahan di antara partai-partai Islam atau yang berbasiskan konstituen Muslim jauh lebih rumit, yang sangat boleh jadi tidak ada hubungannya dengan perbedaan atau khilafiyyah dalam pemahaman praktek keagamaan.†Artinya knowledge interest pada pemikir muslim di Indonesia justru melahirkan banyak friksi, oleh karenanya contest of power di Indonesia tidak hanya antara Islam, Nasionalisme, dan Sekularisme tetapi juga terjadi dalam tubuh internal Islam.
Akhirnya saya sampai di penghujung, tapi seperti biasa tulisan ini hanyalah pengantar dialog dan diskursus yang mesti disambung. Dibalik fenomena ini, sistem politik Indonesia sedang diuji kemampuannya. Nasionalisme sebagai penjaga mekanisme politik akan di hadapkan dengan dilema rakyat yang sedang berubah. Saya ingin sekali memulai tulisan dengan mencontoh Populisme Islam Turki yang lahir dari Rahim dialektika Fundamentalisme dan Sekularisme dan kemudian menjadi anthitesa dari Clash of Civilization Huntington, bisakah Indonesia demikian? Atau jangan-jangan berita itu belum sampai sehingga pandangan yang muncul adalah Xenophobia atau ketakutan akan gerakan Islam? Saya sadar klo corak populisme Islam di Indonesia berbeda, tesis saya juga demikian, tapi alasannya menjadi kocak jika argumentasi akademiknya malah Xenophobia. Dalil itu milik para politisi sebagai wacana propaganda, anda gunakan itu, anda sedang merekrut dan mencari suara untuk pemilu.
Sebagai tambahan saya kira tidak usah diperdebatkan bahwa HTI telah dibubarkan, artinya dia adalah organisasi terlarang. Larangannya apa? Klo itu adalah kegaduhan fisik, saya sepakat. Jika itu perbedaan ideology, maka kita harus mmendudukannya dalam kerangka yang sama ketika Nasionalisme hadir sebagai sinkretis bangsa-bangsa (Baca: Jawa, Sumatra, Kalimantan dll) saat itu. Tapi lagi-lagi itu perdebatan dalam konteks yang lain, namun saya kira hak dari komunitas dilindungi oleh Hukum meski ia tidak muncul dalam teks formal hukum, terlepas bendera itu symbol HTI atau bukan, tapi lagi-lagi saya hendak sampaikan bahwa tak ada satu pun tanda yang dapat menjelaskan keutuhan fenomena, bahkan Luthfi yang dianggap orang punya kemungkinan berubah, artinya tanda Luthfi justru tak bisa menjelaskan Luthfi secara utuh. Kata Wahib, “aku bukan Wahib, tapi me-Wahibâ€. Bendera diisi oleh kalimat syahadat, saya sepakat bahwa ada klaim HTI terhadap kalimat tersebut, tapi kemungkinan lainnya adalah kalimat itu milik orang lain di luar HTI. Oh itu kepentingan? Artinya anda mesti fair dengan melihat kepentingan pada symbol-simbol yang lain. Oleh karenanya, jangan mau di mobilisir dengan ideology, karena klo anda cukup cerdas untuk mengolah informasi, itu mati konyol namanya bakar bendera bertuliskan kalimat syahadat.
So, ini bukan pembelaan atas kepercayaan ataupun aliran tertentu, bukan juga dukungan terhadap yang lainnya. Saya tegaskan ini sebagai pembelaan bahwa beberapa atau mungkin seluruhnya (tesis mengenai kuantitas ini belum saya uji) manusia hidup bersamaan dengan symbol. Jadi toleransi bukan sebatas senyum tulus, dalam sopan-santun tradisi kita, mesti kiranya memuji pakaian orang lain meskipun kita tahu gak matching. Kenapa? Karena ada kesadaran bahwa setiap orang berhak memilih symbol tertentu, itu gak boleh dalam Islam? Sepakat, kalimatnya negasi terhadap ketergantungan apapun selain Tuhan. Tapi beberapa dari kita butuh medium yang lain, beberapa orang misalnya butuh medium Tasbih dalam berdzikir. Yang jadi masalah kepecayaan itu adalah jika benda mampu menegasikan keberadaan Tuhan, siapa yang dapat mengukur? Ya Tuhan, toh itu hubungan vertikal. Ups, Sorry, Saya gak mau berlama-lama dengan bahasan tersebut, intinya, sampai jumpa di forum diskusi.
Terimakasih.