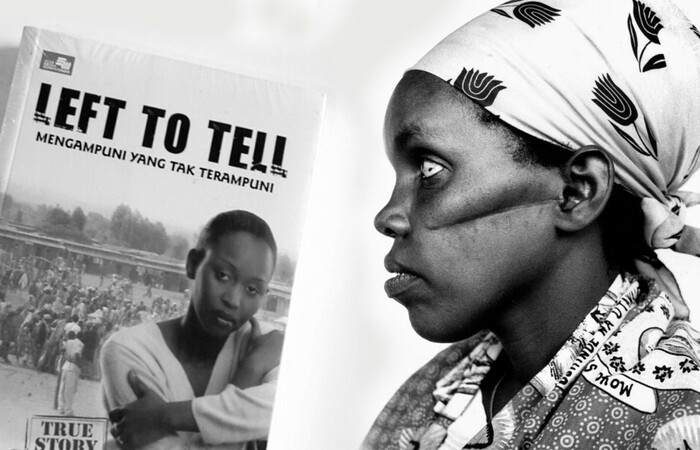Di Indonesia, setidaknya ada dua hal yang segera terasa tak menyenangkan dari sebuah film yang sukses secara komersial. Pertama, film itu tak selalu baik secara kualitas. Kedua, film itu selalu mudah menjadi “negatif trendâ€â€”dalam artian; memicu ramainya “kreatifitas-duplikatif†atau “kelatahan-kelatahan tak perlu†pada produksi film-film setelahnya.
Dari sanalah, film tidak lagi dihadirkan sebagai “perspektif lain†yang tak umum. Tentu, dengan sendirinya, apa yang disebut Joko Anwar dengan “literasi penonton†juga tidak terjadi. Publik film terus menjadi medan pertaruhan (atau kurasi selera) yang justru tidak mampu memangkas jarak antara film baik dan film laris.
“Hanya ada film baik dan film buruk,†kata Mira Lemana. Salah satu sosok penting industri perfilman Indonesia ini, tidak percaya dengan adanya dikotomi “film idealis†dan “film komersilâ€. Sebagai penonton tulen, saya sepakat, meski tak sepenuhnya. Sebab, dengan masih tersedianya “penonton yang tak literatif†tersebut, pada akhirnya, juga menimbulkan persoalan lain: suburnya film “yang penting lakuâ€. Dan terbentuklah sirkulasi setan yang menciptakan pasar sebagai habitat bagi sejenis ekspansi produser bejat.
Tetapi dalam proses “pembacaan karya filmâ€, keyakinan Mira Lesmana di atas, agaknya, cukup menolong agar tidak terjebak pada kategori penonton yang menaruh sinisme berlebihan atas pasar dan pembelaan berlebihan atas ide. Saya kira, tidak semua film laris berkualitas buruk dan tidak semua film idealis dikerjakan dengan beres. Sering muncul “keganjilan†yang sebaiknya diperiksa lebih lanjut, lebih seksama.
Kita tentu masih ingat; setelah Melly Goeslow sukses mengisi soundtrack AADC (2002), lagu-lagunya memenuhi banyak judul film—hampir tiap tahun ada: Eiffel I’m in Love (2003), Apa Artinya Cinta (2005), Heart (2006), Love is Cinta (2007), The Butterfly (2007), Ayat-Ayat Cinta (2008), dan Ketika Cinta Bertasbih (2009). Ruang dengar seperti kehilangan variasi dalam trend—yang selanjutnya memberi bonus “ke-tak-wajar-an†lain. Bahwa ilustrasi musik harus dalam sebentuk lagu dan tanpa memakai jasa Melly, sebuah film, seolah-olah dianggap “bagai dangdut tanpa goyangâ€.
 Salah satu scene dalam film HEART (2006). Sumber gambar: http://www.indonesianfilmcenter.com
Salah satu scene dalam film HEART (2006). Sumber gambar: http://www.indonesianfilmcenter.com
Atau ketika Jelangkung (2001) mendapat respon luar biasa di pasaran. Tak lama kemudian, film horor bergentayangan. Hantu menjadi tokoh figuran yang terlalu sering muncul. Judul-judul yang sebelumnya tak terbayangkan berjubel dalam bioskop; Hantu Jeruk Purut (2006), Hantu Perawan Jeruk Purut (2008), Nenek Gayung (2012) dan Kembalinya Nenek Gayung (2013); Suster Ngesot (2005), Suster N (2007), Pocong 3 (2007), Kuntilanak 2 (2008), Pocong vs Kuntilanak (2008), Kepergok Pocong (2011), Suster Keramas 2 (2011); sedari film Kafir (2002) sampai Pocong Bugil (Eh! Ada nggak sih judul ini Hehehe...). Sebenarnya cukup menahan muak, menjajar judul film horor Indonesia. Seperti daftar kabar buruk yang tak pernah berakhir.
Materi “Jelangkung†bahkan terkloning hingga lima judul film: Jelangkung (2001), Tusuk Jelangkung (2003), Jelangkung 3 (2007), Tumbal Jailangkung (2011), Kalung Jailangkung (2011). Anda boleh menghitung, ada berapa judul film yang mencatut kata “hantu†juga “pocongâ€. Dan semuanya buruk. Hingga “seorang Joko Anwar†mungkin merasa perlu turut andil dengan memproduksi Pintu Terlarang (2009). Sutradara yang identik dengan ide nyentrik itu seakan ingin berkata, “Gini lho cara bikin film horor!â€.
Saya kira, Indonesia cenderung buruk dalam penggarapan film bergenre horor. Asal-muasal “kegaiban†masih didominasi semacam narasi dendam yang seringkali klise dan adegan-adegan “Ci-Luk-Ba†yang terlampau boros. Tak jarang, “sosok hantu†yang dipakai hanya tempelan, tidak sublim dalam kekuatan ceritanya . Karakterisasi horornya terus bertumpu pada wajah rombeng nan melotot. Mirror (2005), tentu pengecualian. Meskipun tidak tergarap matang, film ini memuat ide “fiksi-horor†yang cukup menarik. Sejauh yang saya tahu, memang belum ada film horor Indonesia yang tampil dengan kualitas betul-betul meyakinkan.
Parade film horor baru terasa menyusut (atau kehilangan magnet pasarnya) setelah Hanung “panen besar†melalui Ayat-Ayat Cinta (2008). Dan musim pun berubah; sosok-sosok berjilbab serupa “wallpaper bergerak†segera memenuhi (terlalu) banyak judul film—dibarengi film ber-“latar†luar negeri yang sangat mungkin diedit ulang menjadi video promo wisata sebuah travel-agent. Atau iklan bisnis fashion. Perempuan Berkalung Sorban (2009), untuk pengeculian; film ini masih menawarkan apa yang saya sebut sebagai “perspektif lainâ€.
Plot nyaris persis berulang ketika Hanung kembali sukses merampok minat menonton dengan menggarap Sang Pencerah (2010). Di sesi bio-pic ini, giliran pesohor (nyaris legendaris) dalam dunia perfilman Indonesia yang turut terseret arus: Garin Nugroho, tiba-tiba, nampak sebagai sosok sutradara yang lumrah—Soegija (2012) menjadi film termahal yang pernah dikerjakannya (ketika itu) sekaligus film pertama yang “Sangat-Amat-Nggak-Garin-Bangetâ€.
 Sepenggal adegan dalam film OPERA JAWA (2006). Salah satu film masterpiece Garin Nugroho. Sumber gambar: http://catalogue.globalfilm.org
Sepenggal adegan dalam film OPERA JAWA (2006). Salah satu film masterpiece Garin Nugroho. Sumber gambar: http://catalogue.globalfilm.org
Tema bio-pic movie segera ramai, menggenapi bukti dari apa yang di awal saya sebut dengan “kelatahan-kelatahan tak perluâ€. Masih segar dalam ingatan; ketika Jokowi berhasil menjadi figur politik yang menyedot percakapan publik, bahkan mampu menembus “gosip selebriti†(fenomena yang sangat jarang), tak lama kemudian, muncul film Jokowi (2013)—yang digarap dengan amat biasa, dengan kesan riset tak serius, dan kisah yang dihadirkan juga tidak cukup kuat menggugah penonton.
Sebenarnya, pada tahun 2005, Miles Produktions berhasil me-refresh dunia perfilman dengan meluncurkan bio-pic movie GIE. Selang tiga tahun, hadir lebih menggebrak melalui Laskar Pelangi (2008). Kedua film itu diadaptasi dari Catatan Harian Soe Hok Gie dan novel laris Andrea Hirata. Kesuksesan itulah yang justru kian memperjelas posisi Hanung Bramantyo sebagai trend-setter. Pasalnya, rentetan film bio-pic baru terasa setelah Sang Pencerah (2010) dan film adaptasi baru terasa setelah Perahu Kertas (2012).
Film adaptasi, memang bukan jenis baru paska bangkitnya film Indonesia dari mati suri. Tetapi, sejumlah film adaptasi hadir dalam bentang durasi untuk gejala lain. Misalnya, Ketika Cinta Bertasbih (2009); ia lebih memperlihatkan pengaruh dari munculnya “sosok berjilbab†atau sedang diminatinya kisah cinta berlatar agama (islam) dalam sebuah film. Perahu Kertas memulai trend yang berbeda. Film yang diangkat dari novel Dewi Lestari ini juga turut melesatkan nama sang penulis. Karya-karya “Dee†secara beruntun kemudian diangkat ke layar lebar; Rectoverso (2013), Supernova (2014), Filosofi Kopi (2015). Dewi Lestari seperti menggantikan sosok Melly Goeslaw dalam versi kesusasastran. Sindrom yang sama, saya kira, juga telah menjangkiti Chicco Jerikho dan Reza Rahardian.
Tetapi apakah film yang mengikuti trend otomatis buruk? Tentu tidak. Ada dua cara sederhana untuk memastikannya. Pertama, dengan mempertimbangkan jeda, atau perkiraan waktu penggarapan, antara film terbaru dan film terdekat sebelumnya yang bertema/bergenre serupa. Kedua, dengan menontonnya lebih dari satu kali. Cara yang kedua, saya kira, lebih bijak dalam menjawab; apakah sebuah film diproduksi untuk sekedar mengambil donasi penonton atau ingin hadir sebagai “perspektif lainâ€, apakah film tersebut memiliki tawaran literatif atau cenderung mengidap sebentuk “kreatifitas-duplikatif†di dalam trend? Salah satu yang menurut saya berhasil: Filosofi Kopi (2015).
Film yang sebenarnya ikut menjadi follower dari trending-nya skenario adaptasi karya Dee Lestari (dan tentu, industri kedai kopi) ini, mampu menampilkan kekuatannya tersendiri. Penulis skenario, Jenny Jusuf, tak terjebak fiksionalitas Dee Lestari, sekaligus sanggup menyelamatkan “rasa sastraâ€-nya. Ping-Pong dialog dalam film terdengar wajar, sehari-hari. Kutipan-kutipan langsung dari cerpen yang diadaptasinya ditempatkan dengan tepat. Literasi tentang kopi juga ditampilkan dengan mencukupi.
Sebagai film adaptasi dari penulis sastra yang dikenal penuh sentimentalia, Filosofi Kopi terkemas dalam kadar dramatik yang tak berlebihan. Tetapi film besutan Angga Dwimas Sasongko ini tidaklah ompong dari momen emosional. Di bagian awal scene misalnya; kemarahan Jody ketika Ben dengan entengnya mempersalahkan Bapak Jody yang telah meninggal dunia atas tunggakan utang yang harus mereka tanggung, kemudian berlanjut dengan adegan monolog di tempat cukur rambut. Atau kilasan ingatan Ben ketika mengunjungi kebun Pak Seno. Atau dokumentasi masa kecil Ben dan Jody; ketika mereka memainkan peran barista di dapur rumah.
Meski secara keseluruhan sudah baik, film yang diakui sendiri oleh penulis cerpennya sebagai adaptasi yang paling ia suka ini, masih menyisakan sejumlah hal yang bagi saya agak mengganggu. Style kamera goyang, sudut pengambilan gambar, permainan zoom-in zoom-out, di beberapa bagian terasa tidak pas dan tidak memiliki motif memadai. Sehingga alasan atas dipakainya teknik kamera tersebut tak mampu saya pahami. Dua adegan krusial terasa mengganjal. Agak tanggung. Pertama, pilihan dan ping-pong dialog pada saat El meliput Perfecto. Kedua, adegan dalam mobil setelah Ben dan Jody memenangkan sayembara; di momen Ben berpamit (ingin pensiun dini sebagai barista) inilah, Chicco Jerikho menampilkan akting terburuknya dalam Filosofi Kopi.
 Chicco Jerikho (Ben) dan Rio Dewanto (Jody) dalam salah satu adegan Filosofi Kopi. Sumber gambar: http://cdn.img.print.kompas.com
Chicco Jerikho (Ben) dan Rio Dewanto (Jody) dalam salah satu adegan Filosofi Kopi. Sumber gambar: http://cdn.img.print.kompas.com
Juga kehadiran El—yang tak punya cukup porsi untuk membuat perannya lebih bernyawa; patut disayangkan. El terkesan sebagai pelengkap, atau tokoh yang ditambahkan setelah plot skenario jadi; yang hadir hanya untuk mengantar Ben dan Jody pada kopi Tiwus. Perjalanan menuju Ijen yang tak menampilkan Ijen dan justru kebun teh, bagi saya yang pernah ke Ijen, cukup mengecewakan.  Tentu, lebih kecewa lagi ketika part di warung Pak Seno berakhir: “Kenapa tak sedetail adegan indoor, di kedai kopi, atau se-intens pertengkaran-pertengkaran Ben dan Jody? Mulai dari set-artistik, komposisi gambar, sampai tanggungnya penggarapan scene memori masa kecil Ben.â€
Tetapi film berdurasi hampir dua jam ini juga sukses menyisipkan sejumlah kritik yang dikemas apik, nyaris jenaka—yang baiknya tak luput dari perhatian anda; misal ucapan Ben saat beberapa remaja batal ngopi hanya sebab tak tersedianya fasilitas wifi, “Dasar ABG labil!â€; atau yang ini, “Kalau perlu kita buka 24 jam sekalian, biar kayak starbauck!â€; atau ucapan beraroma eksistensial dari Jody ini, “Gila, Tuhan juga capek sama elo!†Meski sayang, di tengah cerita kembali muncul suatu hal yang tak nyaman diterima nalar, sebentuk pemaksaan konten.
Cukup sukar buat saya mencari kaitan antara penggusuran, kebun kopi, dan lahan sawit. Sejauh yang saya tahu, kebun kopi umumnya terhampar pada tanah agak tinggi, atau lereng-lereng bukit, sedangkan sawit pada tanah rendah yang datar. Misalnya kopi arabika; akan tumbuh baik bila ditanam pada ketinggian 800 – 1500 Mdpl. Sementara sawit, hanya tumbuh baik bila ditanam pada ketinggian kurang dari 600 Mdpl dan tanah berkontur datar. Tetapi saya ingat, ketika film ini rilis, bencana kabut asap akibat dari pembakaran lahan secara sengaja tengah santer diperdebatkan banyak pihak. Para pengusaha perkebunan sawit dianggap sebagai biang kerok. Dari ingatan itu, segera saya dapat penjelasan: “kegenitan politis!â€.
Memang, di sejumlah tempat terjadi isu penggusuran dan skandal agraria berkepanjangan; menyangkut sawit, media seringkali memakainya untuk kebutuhan framing semata-mata (demi menjangkau minat pembacanya)—tanpa kejelasan rinci tentang "alih lahan" yang kemudian menimpa konflik tanah bersangkutan. Ketinggian tanam ideal bisa terus berubah seiring pemanasan global, atau memiliki hitungan khas yang tak selalu sama dengan tempat lain pada umumnya sebab anomali iklim lokal; dan memang, ada irisan lahan, ketinggian tanah ideal, antara jenis kopi robusta dan sawit, tapi dalam film yang mendapat beberapa nominasi dalam gelaran Piala Citra 2015 ini, indeks-fiksinya jelas: suasana warung Pak. Seno yang adem, letak ketinggian tanah yang di dahuluhi kebun teh (tanpa pohon pelindung; berarti elevasi tanahnya sedang, atau tinggi), juga ijen sebagai referensi naturalnya. Dan tentu, sulit membayangkannya berada di dataran rendah dengan ketinggian di bawah 600 mdpl.
Terlepas dari sederet keganjilan tak filosofis di atas, mungkin yang paling berharga dari Filofosi Kopi; film ini mampu menghadirkan "kopi" bukan sebagai "produk" dan “ngopi†bukan sebagai “kesibukan konsumtifâ€. Melalui tokoh Ben, Filofosi Kopi hadir sebagai sebentuk penghayatan; cara menyesap filosofi dari apa yang kita kerjakan sehari-hari. Seperti apa yang dikatakan Ben ketika berdebat dengan Jody, “Kopi yang enak akan selalu menemukan penikmatnya.†Seperti juga hidup, yang dijalani dengan penuh diri; akan selalu menemukan nasib baiknya sendiri, jenis keberuntungannya sendiri, jenis kebahagiaannya sendiri.[]