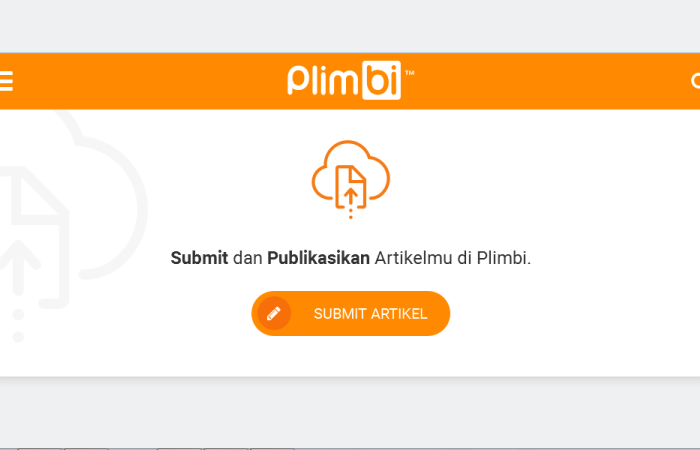Bermimpi pun tidak pernah, bahwa saya(penulis) dan para warga harus meninggalkan desa tercinta yang oleh leluhur kami diberi nama Jatirejo. Sebab disanalah kami bertahun-tahun membangun kehidupan sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang berperadaban. Jatirejo adalah sebuah desa kebanggan yang terletak ditengah-tengah garis segi tiga antara desa siring, desa mindi, dan desa besuki.
               Di wilayah kecamatan porong, desa kami sangat diperhitungkan. Bahkan menjadi barometer karena banyak tokoh masyarakat yang disegani kala itu yang bermukim didesa kami. Warga jatirejo tergolong masyarakat menengah ke atas, tetapi tetap menjaga serta melestarikan nilai-nilai luhur kehidupan masyarakat pedesaan.

(Makam tokoh yang sudah terendam lumpur *sebelum renovasi)
        Apabila seorang warga meninggal dunia, warga yang lainya akan berduyun-duyun berta’ziah. Yang paling menarik adalah ketika musim panen tiba, para buruh tani yang membantu menuai padi tidak diberi ongkos uang tunai, tetapi diberi sekarung padi. Itulah diantara wujud harmoni kehidupan warga desa kami.
               Kami hidup dalam kebersamaan, saling menolong serta selalu bergotong royong seperti yang lazimnya dilakukan masyarakat pedesaan. Kami tidak menganggap perbedaan sebagai persoalan. Kami sangat menghargai perbedaan pendapat dan sama-sama saling memberi ruang serta jalan bagi perbedaan tersebut, sehingga hampir tidak pernah terjadi gesekan atau ketersinggungan.
               Namun, sendi-sendi kehidupan yang telah dibangun secara turun temurun itu harus musnah akibat ditenggelamkan oleh lumpur panas lapindo sejak tanggal 12 juni 2006. Ya, hampir 10 tahun desa kami hilang ditelan lumpur. Desa yang semula melambai penuh keanggunan dan keelokan, kini menjelma menjadi danau lumpur yang menyeramkan. Hati saya semakin pedih dan jiwa saya terasa terkoyak-koyak setelah banyak orang justru menjadikan desa kami sebagai obyek wisata atau sekedar tontonan.

(Wisatawan Lumpur didesa Jatirejo)
               Kami dipaksa keluar dari tanah kelahiran kami. Desa yang membesarkan saya dan warga desa yang lainya. Lebih dari 9 tahun ini kami terjajah dan tergusur dari desa kami sendiri. Tak hanya itu, lumpur lapindo juga mengakibatkan warga jatirejo terpecah-pecah, tercerai-berai, dan bertebaran dimana-mana. Kami semua telah kehilangan sanak saudara dan para tetangga. Sering kali anak-anak yang mengalami tekanan jiwa tak betah dipengungsian, apabila sudah seperti itu anak-anak kemudian menangis seraya merengek kepada orang tuanya. Mereka selalu bertanya “kapan kita akan kembali ke jatirejo, ayah?†dan banyak pertanyaan lain yang tidak mungkin dapat dijawab oleh orang tua mereka.
               Tenggelamnya desa kami membuahkan banyak peristiwa tragis dan memilukan. Bahkan prediksi para ahli, lumpur akan berhenti dengan sendirinya memerlukan waktu 20 – 31 tahun semakin menggoncangkan perasaan warga. Terutama warga desa jatirejo yang desanya sudah hancur lebur dibawah lumpur. Harapan semula mulai nampak terang, lambat laun meredup dan tenggelam.
               Mungkinkah desa kami akan tinggal kenangan? Atau bahkan desa kami hanya tersisa cerita yang mengenaskan. Banyak tanya yang sulit menemukan jawaban, banyak keinginan yang kurang mendapat perhatian. Sedangkan semburan lumpur masih terus berjalan.
 (Kubah masjid didekat rumah penulis)
(Kubah masjid didekat rumah penulis)
~ Kedamaian yang terusik
               Saya dan seluruh warga jatirejo tidak pernah merasa benar-benar “merdeka†sejak lumpur lapindo perlahan-lahan mengusik kami. Malam-malam yang kami lalui terasa begitu panjang, meski tidur semakin pendek. Banyak orang yang lalu lalang membicarakan lumpur panas ini, akan tetapi semakin sering dibicarakan, nyata sekali pembahasan mengenai lumpur selalu berputar-putar ditempat yang sama.
Segala kejenuhan dan kejengkelan mulai hinggap dalam dada setiap warga. Semula yang berkawan denga karib, tetapi hanya karena persoalan tanggul, telah meretakan pertemanan mereka, hanya karena perbedaan opsi atau pilihan bentuk penyelesaian, telah mencabik-cabik persaudaraan warga, dan hanya persoalan sepele saja telah menimbulkan rasa suka dan tidak suka.Kondsi semakin memprihatinkan, perasaan sensitif semakin menguasai hati warga korban lumpur. Namun adakah insan yang peduli?
Orang-orang yang kebetulan memiliki hak waris, mulai mengkalkulasi seberapa besar ganti untung yang akan diperoleh, meski dilain pihak ada ahli waris yang lain yang dengan sekuat tenaga mempertahankan prinsip bahwa harta peninggalan harus atas nama dirinya. Ada pula yang menginginkan bahwa warisan harta benda yang saat itu terendam lumpur harus dijual segera, sebab jatirejo sudah tidak layak untuk dijadikan tempat pemukiman jangka pendek maupun jangka panjang.

Keadaan berbalik seratus delapan puluh derajat. Warga korban lumpur kini terpetak-petak dalam berbagai keinginan. Ada yang ingin mempertahankan desanya, sejengkalpun tidak ada niat untuk menjual tanah leluhurnya. Ada pula yang ingin segera meminta ganti rugi sekaligus menjual dengan harga yang sangat fantastis. Namun ada pula yang tidak memilih kedua-duanya. Mereka mengajukan relokasi atau restlement meski bersifat sementara.
Semua ini telah menjadikan pandangan warga jatirejo kepada sesama warga telah berubah menjadi tatapan kecurigaan atau cenderung mengaah pada sikap sinis, sungguh telah hilang senyum hangat yang selama ini dimiliki warga. Ternyata lumpur lapindo telah berhasil menkoyak-koyak pranata sosial yang telah bertahun-tahun dibangun. Berhasil pula membangun opini perpecahan antar warga, berhasil membuat shock therapy sehingga warga ketakutan karenanya. Namun sekali lagi, siapakah insan yang peduli?
Uang adalah senjata utama untuk mencabik-cabik keutuhan. Uang mulai berbicara karena uang mengerti betul keadaan warga di desa kami. Sehingga ia harus tampil atau sengaja ditampilkan untuk mendiamkan warga korban lumpur.
***
Kini, 9 tahun telah berlalu. Banyak dari mereka yang letih berjuang demi kemerdekaan dan ada pula yang masih berjuang karena serakah dan masih kurang. Hanya segelintir orang yang masih mengingat detik-detik kehilangan. Kebanyakan mereka semua melupakan kenangan. Karena Hukum, telah dibeli dengan uang. Walau harus merdeka tanpa tanah kelahiran.
Â
Â

![Film Warkop DKI Reborn [2016]](http://srv1.portal.p-cd.net/700x450/2016/04/06/164062-1459910311-677347.jpg)